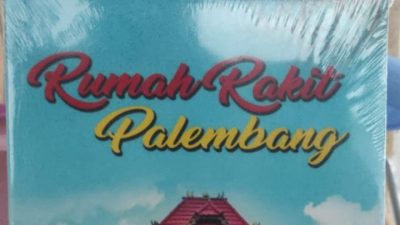Gandustv.com, Palembang – Istilah alumni perguruan tinggi dalam keadaan tidak baik baik saja saat ini bukan lah omongan semata atau lelucon tetapi ungkapan realitas betapa sulitnya para alumni itu mencari pekerjaaan dan atau bersaing di pasar kerja. Ironinya satu sisi perguruan tinggi berlomba dan bersaing ketat mengejar predikat unggul di setiap sector penilaian akreditasi.. Ada titik otokritik yang coba dibangun para alumni dengan istilah dimaksud yakni peran serta perguruan tinggi ikut andil memikirkan para alumninya mampu bersaing di pasar kerja global, bukan semata menghasilkan produk alumni unggul , dengan pujian dan seatribut pujian-pujian bagi lainnya bagi alumni.
Perubahan dunia kerja di era digital menuntut lulusan perguruan tinggi untuk tidak hanya menguasai kompetensi akademik (hard skills), tetapi juga memiliki soft skills dan life skills yang kuat. Data dari Graduate Employability Survey (British Council, 2018) menunjukkan bahwa 53% pemberi kerja di Indonesia kesulitan menemukan lulusan dengan keterampilan nonteknis yang memadai, sementara 75% di antaranya menilai kemampuan komunikasi, kreativitas, pemecahan masalah, dan kerja tim sebagai kompetensi paling penting. Laporan LinkedIn 2025 juga menegaskan bahwa 32% perekrut di Indonesia menganggap kekurangan soft skills—seperti komunikasi dan problem solving—sebagai hambatan utama dalam perekrutan tenaga kerja. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi pada Februari 2025 mencapai 6,23%, menandakan bahwa ijazah semata belum menjadi jaminan kesiapan kerja di dunia nyata.
Menurut BPS (2025), secara nasional jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang atau 4,76% dari angkatan kerja. Namun, kesenjangan antar daerah masih tinggi—Papua (6,92%), Kepulauan Riau (6,89%), dan Jawa Barat (6,74%) mencatat tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Ketimpangan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja di sektor formal. Dalam konteks ini, kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, dan bekerja sama lintas disiplin menjadi indikator penting kesuksesan karier, yang semuanya termasuk dalam kategori soft dan life skills.
Khusus di Provinsi Sumatera Selatan, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2024 tercatat 3,86%, menurun dari tahun sebelumnya. Namun, data menunjukkan bahwa pengangguran terbanyak berasal dari lulusan SMA (107.766 orang) dan perguruan tinggi (34.481 orang). Lebih mencemaskan lagi, lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran tertinggi dengan TPT mencapai 10,53%. Kondisi ini memperlihatkan adanya mismatch antara keterampilan yang diperoleh di kampus dengan kebutuhan pasar kerja di wilayah tersebut. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan soft skills seperti komunikasi efektif, manajemen waktu, kerja sama tim, dan adaptabilitas menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan angka pengangguran terdidik di daerah.
Dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan ke-4 (Pendidikan Berkualitas) dan Tujuan ke-17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), penguatan soft skills dan life skills harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan tinggi. Perguruan tinggi perlu membangun kemitraan strategis dengan dunia industri, pemerintah, dan masyarakat guna menyusun kurikulum adaptif, membuka peluang magang, serta mengembangkan experiential learning yang relevan dengan kebutuhan global. Penelitian terbaru (Embiss, 2024) menegaskan bahwa soft skills memiliki korelasi positif signifikan terhadap persepsi kesiapan kerja mahasiswa, menunjukkan bahwa lulusan yang dibekali keterampilan interpersonal dan kepemimpinan lebih mudah terserap di dunia profesional.
Dengan demikian, arah transformasi pendidikan tinggi tidak lagi sekadar mencetak sarjana berijazah, melainkan membentuk human capital yang cerdas, tangguh, dan berkarakter. Dalam konteks SDGs, perguruan tinggi perlu menjadi pusat kolaborasi dan inovasi yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, berempati sosial, serta mampu memecahkan masalah kompleks di tengah perubahan global. Kolaborasi antara kampus, industri, dan masyarakat bukan hanya memperkuat ekosistem pembelajaran, tetapi juga menjembatani lulusan agar benar-benar siap menghadapi dunia kerja yang dinamis dan berkelanjutan.
Fenomena ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja mencerminkan adanya kesenjangan sistemik dalam pendidikan tinggi Indonesia. Meskipun kurikulum nasional telah diarahkan pada Outcome-Based Education (OBE) dan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), implementasinya di banyak perguruan tinggi masih cenderung berorientasi pada capaian kognitif, bukan pada penguatan kompetensi afektif dan psikomotorik. Hal ini menjelaskan mengapa lulusan berpengetahuan tinggi belum tentu memiliki kesiapan kerja yang optimal, karena belum terbiasa berinteraksi dalam konteks dunia nyata yang menuntut fleksibilitas, kolaborasi, dan ketangguhan sosial.
Menurut kerangka Sustainable Development Goals (SDG) 4, pendidikan tinggi yang berkualitas tidak hanya diukur dari jumlah lulusan, tetapi dari sejauh mana universitas mampu menciptakan transformasi sosial melalui pemberdayaan manusia. Artinya, kampus harus berfungsi sebagai learning ecosystem yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam satu sistem pembelajaran. Soft skills seperti komunikasi lintas budaya, empati sosial, dan kepemimpinan kolaboratif merupakan jembatan penting untuk mewujudkan kualitas manusia berdaya saing global namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal.
Data BPS Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pengangguran terbesar justru berasal dari kelompok usia produktif dengan tingkat pendidikan tinggi. Ini menandakan bahwa masalah utama bukan pada kekurangan lapangan kerja semata, tetapi pada ketidaksiapan mental, sosial, dan profesional lulusan dalam beradaptasi dengan pasar kerja yang cair dan kompetitif. Hal ini menuntut paradigma baru pendidikan tinggi yang tidak hanya menekankan pada transfer of knowledge, tetapi juga formation of character dan transformation of mindset.
Kemitraan strategis antara universitas dan dunia kerja menjadi solusi yang paling realistis.
Melalui kolaborasi dengan industri, kampus dapat merancang kurikulum berbasis real-world problem, memfasilitasi internship yang terarah, serta menyediakan ruang project-based learning yang menumbuhkan kreativitas dan tanggung jawab sosial mahasiswa. Selain itu, kemitraan lintas sektor dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial dapat membuka peluang pembelajaran kontekstual berbasis masyarakat. Inilah bentuk nyata dari penerapan SDG 17 (Partnership for the Goals) dalam konteks pendidikan. Secara sosiologis, penguatan soft skills dan life skills juga dapat dipandang sebagai bentuk modal sosial (social capital) yang mempengaruhi keberhasilan individu di pasar kerja.
Teori Pierre Bourdieu menyatakan bahwa selain economic capital (modal ekonomi) dan cultural capital (modal budaya), social capital memainkan peran penting dalam membangun jaringan, reputasi, dan kepercayaan profesional. Dalam konteks Indonesia, mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan, kegiatan sosial, dan proyek kolaboratif seringkali memiliki kemampuan adaptif dan kepemimpinan yang lebih tinggi dibanding mereka yang hanya fokus pada pencapaian akademik semata.
Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar tidak hanya mencetak lulusan berijazah, tetapi juga membentuk insan yang siap menghadapi dunia kerja dan kehidupan sosial secara berkelanjutan. Dalam konteks capaian SDGs, khususnya tujuan pendidikan berkualitas dan kemitraan untuk pembangunan, kampus dituntut memperkuat pengembangan soft skills dan life skills mahasiswa agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja yang dinamis. Data BPS 2024 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMA dan perguruan tinggi, menandakan adanya kesenjangan antara kompetensi akademik dan kebutuhan industri. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, perguruan tinggi perlu memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), membangun pusat karier yang aktif, serta menyediakan program pembelajaran berkelanjutan (lifelong learning) bagi alumninya.
Selain itu, penting bagi kampus untuk mengembangkan jejaring alumni (IKA ALUMNI), program mentoring, dan inkubasi kewirausahaan yang memberi ruang bagi lulusan agar tidak hanya mencari kerja, tetapi juga menciptakan lapangan kerja.
Dengan strategi tersebut, perguruan tinggi dapat memainkan peran strategis dalam mencetak generasi unggul yang adaptif, berkarakter, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan’
Dengan demikian, analisis empiris dan teoretis menunjukkan bahwa soft skills dan life skills bukan pelengkap, melainkan fondasi utama dalam membangun kesiapan kerja dan keberlanjutan karier lulusan. Perguruan tinggi yang mampu mengintegrasikan pembelajaran berbasis pengalaman, kemitraan industri, dan nilai-nilai kemanusiaan akan menjadi motor penggerak SDGs 4 dan 17 secara nyata.
Dr. Mohammad Syawaludin. MA
Dosen pascasarjana UIn Raden Fatah Palembang
Dari Kampus ke Dunia Kerja: Penguatan Soft Skills dan Life Skills Lulusan Perguruan Tinggi dalam Kerangka SDGs Pendidikan dan Kemitraan